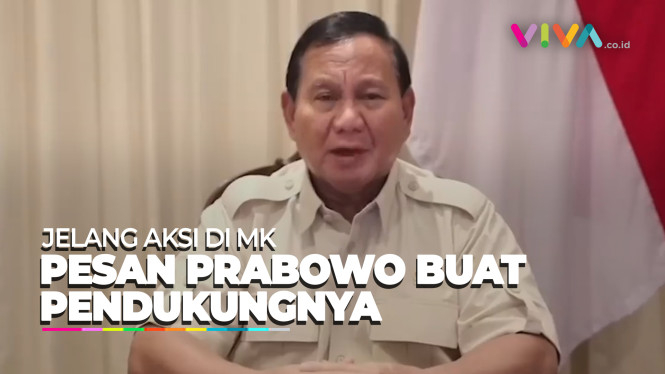Sumber :
VIVAnews
– Sebuah sekolah menengah atas (SMA) di Kota Batu, Jawa Timur, tidak hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran umum. Sekolah bernama SMA Selamat Pagi Indonesia itu mengajarkan toleransi atas perbedaan suku, agama, dan ras kepada seluruh siswanya.
Sekolah itu sengaja menerima siswa dari ragam suku, agama, dan daerah. Mulai suku Jawa, Sunda, Makassar, Maluku, Aceh, Madura, Papua, Tionghoa, dan lain-lain. Lima agama yang diakui di Indonesia terwakili pada 123 siswa di sekolah itu.
Para siswa, yang seluruhnya tinggal di asrama, tidak hanya menerima ajaran sikap saling menghormati tetapi sekaligus menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. Seperti pagi itu, Stefani Ditya Kristanti kebagian tugas memimpin doa di depan kelas. Siswi kelas 12 asal Pacitan, Jawa Timur, meminta izin memandu teman-temannya berdoa sesuai tata cara agamanya, Kristen Protestan. Sebanyak 38 siswa lain di kelasnya segera menundukkan kepala dan berdoa mengikuti aba-aba Stefani, namun dengan cara sesuai agama masing-masing.
“Setiap pagi sebelum memulai pelajaran selalu dimulai dengan berdoa, setiap siswa dapat giliran memimpin doa,” katanya, Selasa, 25 November 2014.
Stefani adalah satu dari 38 siswa kelas 12 di SMA Selamat Pagi Indonesia. Dia adalah satu dari tujuh siswa beragama Kristen di angkatannya. Lainnya ada 16 siswa beragama Islam, delapan siswa beragama Katolik, empat siswa beragama Hindu, dan tiga siswa beragama Budha.
Komposisi serupa di setiap angkatan sejak SMA tersebut berdiri tahun 2007 silam. Stefani harus bergiliran dengan kawan dari agama lain untuk membaca doa di awal belajar setiap hari.
Sekolah itu sengaja menerima siswa dari ragam suku, agama, dan daerah. Mulai suku Jawa, Sunda, Makassar, Maluku, Aceh, Madura, Papua, Tionghoa, dan lain-lain. Lima agama yang diakui di Indonesia terwakili pada 123 siswa di sekolah itu.
Para siswa, yang seluruhnya tinggal di asrama, tidak hanya menerima ajaran sikap saling menghormati tetapi sekaligus menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. Seperti pagi itu, Stefani Ditya Kristanti kebagian tugas memimpin doa di depan kelas. Siswi kelas 12 asal Pacitan, Jawa Timur, meminta izin memandu teman-temannya berdoa sesuai tata cara agamanya, Kristen Protestan. Sebanyak 38 siswa lain di kelasnya segera menundukkan kepala dan berdoa mengikuti aba-aba Stefani, namun dengan cara sesuai agama masing-masing.
“Setiap pagi sebelum memulai pelajaran selalu dimulai dengan berdoa, setiap siswa dapat giliran memimpin doa,” katanya, Selasa, 25 November 2014.
Stefani adalah satu dari 38 siswa kelas 12 di SMA Selamat Pagi Indonesia. Dia adalah satu dari tujuh siswa beragama Kristen di angkatannya. Lainnya ada 16 siswa beragama Islam, delapan siswa beragama Katolik, empat siswa beragama Hindu, dan tiga siswa beragama Budha.
Komposisi serupa di setiap angkatan sejak SMA tersebut berdiri tahun 2007 silam. Stefani harus bergiliran dengan kawan dari agama lain untuk membaca doa di awal belajar setiap hari.
“Saya jadi hapal doanya orang Hindu, Budha, Katolik, dan Islam. Karena yang bertugas harus memimpin doa sesuai agamanya. Sering juga bertanya tentang ritual ibadah, tetapi tidak mendiskusikan atau mencari yang paling baik karena itu bisa memicu pertengkaran,” katanya.
Bahasa Indonesia
Tak hanya keragaman soal tata cara berdoa, Stefani yang tinggal satu kamar di asrama dengan empat siswa lain asal Kalimantan, Papua, dan Banyuwangi, banyak belajar tentang keragaman dialek dan budaya temannya. Setiap siswa mendapat fasilitas asrama selama menuntaskan pendidikan di SPI.
“Saya baru tahu orang Banyuwangi menyebut singkong itu sawi, sementara di daerah saya sawi adalah nama sayur, dan bagi orang Surabaya sudah biasa menyebut sirah (kepala manusia) dengan endas, sedangkan di tempat saya endas itu sebutan kepala untuk binatang,” kata Fani, sapaan akrabnyanya.
Dari keragaman tersebut, Fani bersyukur ada bahasa Indonesia yang menyatukan seluruh keragaman bahasa. Dia lantas sepakat dengan penghuni asrama lain untuk membatasi penggunaan bahasa daerah dan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia.
“Ada banyak siswa asal pulau Jawa di SMA ini, tapi kami sepakat untuk lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, ini untuk mencegah terjadinya salah paham dan agar tidak ada siswa yang merasa dikucilkan hanya karena mereka tak bisa berbahasa Jawa,” katanya.
Bagi Ridwan Dinar Maleo, berada di antara puluhan siswa dengan agama, suku dan bahasa yang berbeda selama dua tahun terakhir, membuatnya semakin yakin bahwa perbedaan itu baik. Awalnya, remaja asal Bandung itu beranggapan bahwa semua agama adalah salah kecuali Islam. Namun itu berubah setelah bertemu dengan kawan sekamar asal Poso, Sulawesi Selatan, di asramanya.
“Dia bilang dia trauma kalau ketemu orang Islam. Tapi sekarang sudah tidak lagi, semua agama mengajarkan hal yang baik, hanya orangnya yang tidak baik. Itu adalah pelajaran penting yang kami petik dari sini,” ujarnya.
Remaja berkulit langsat itu punya pandangan lain tentang terorisme dan paham organisasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang sedang marak muncul di berbagai media. Menurutnya, tindakan teror yang didasarkan pada agama itu tidak benar. “Itu bukan agamanya yang salah, tapi orang-orangnya.”
Keberagaman dan toleransi yang diajarkan di sekolah tersebut membuat Ridwan bisa memandang perbedaan berkeyakinan dari sudut pandang berbeda. Ridwan merasa bangga bisa terlibat menjadi panitia berbagai perayaan hari besar empat agama lain di sekolahnya setiap tahun. “Kalau ritual ibadahnya itu adalah urusan masing-masing, tapi kami saling membantu dalam perayaannya," katanya.
Bisa bersekolah secara gratis di SMA Selamat Pagi Indonesia memberi banyak pengetahuan baru. Selain betapa beragamnya Indonesia, pengetahuannya soal finansial dan berwiraswasta juga meningkat. Fasilitas yang lengkap mulai dari asrama, kebutuhan sekolah, kesehatan, pengetahuan ekonomi makro di luar jam sekolah, dan uang saku setiap bulan adalah sedikit dari berbagai manfaat yang dirasakan selama berada di SMA itu.
“Awal masuk di sini saya terkejut, biasanya sekolah gratis itu banyak yang minus, ternyata di sini semuanya positif,” katanya.
Sayembara Rp1 miliar
Stefani dan Ridwan adalah dua dari sekitar 123 siswa yang kini menjadi siswa di SMA Selamat Pagi Indonesia. Wakil Kepala Sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia, Didik Tri Hanggono, menyebut sekolahnya menyediakan guru agama dari lima agama yang berbeda. Dia mengaku kesulitan mencari guru agama dari kepercayaan Konghucu yang kini telah diakui keberadaanya oleh negara.
“Persyaratan menjadi guru SMA adalah sarjana, begitu pula dengan guru agama, sampai sekarang kami belum bisa menemukan guru agama Konghucu yang sarjana. Jadi belum menerima siswa dengan kepercayaan Konghucu,” katanya.
Pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia, Julianto Eka Putra, sengaja membuat sekolah gratis dengan komposisi siswa seluruh Indonesia dan dari lima agama yang berbeda. Berbagai peristiwa kekerasan yang berbau kesukuan, agama, ras dan antar golongan (SARA) di Indonesia, menjadi latar belakangnya untuk mendirikan sekolah gratis yang menghargai perbedaan, dengan konsep persatuan nasional, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
Bermodal Rp10 miliar di tahun 2007, pria asal Surabaya itu mulai berinvestasi membeli lahan seluas 3,3 hektare dan membangun dua gedung utama, satu gedung sekolah dan satu gedung asrama.
Setiap tahun, dia membatasi jumlah siswa sekitar 40 anak dengan prioritas anak yatim-piatu, yatim, keluarga tidak mampu dan dari berbagai daerah serta agama yang berbeda. Komposisinya 40 persen Islam, masing-masing 20 persen untuk Kristen dan Katolik, dan masing-masing 10 persen untuk Hindu dan Budha.
Dari 123 siswa di kelas 10 sampai 12, sekitar 52 persen atau 64 siswa di antaranya berasal dari tiga provinsi di Jawa, disusul 13 persennya dari berbagai provinsi dari Sulawesi dan Kalimantan. Lainnya ada dari Madura, Maluku, Papua hingga Aceh. Informasi perekrutan siswa disebarkan lewat jaringan bisnisnya dan lewat berbagai media sosial .
Presiden Komisaris sebuah perusahaan dengan 22 divisi usaha itu percaya bahwa keberagaman dan perbedaan tidak hanyay baik, tetapi dibutuhkan. “Setiap tahun saya selalu memberikan sayembara: siapa saja siswa saya yang bisa menemukan benda hidup atau benda mati dua saja, yang serupa satu dengan yang lain, akan saya beri uang Rp1 miliar. Sayang sampai sekarang sayembara ini belum terpecahkan.”
Dituduh kristenisasi
Upayanya untuk berdamai dengan perbedaan tidak mudah. Tahun 2010, upayanya sempat dituduh sebagai upaya kristenisasi oleh penduduk sekitar Pandanrejo, Kota Batu. “Ibu asrama saat ke pasar ditanya oleh pedagang, sedang apa belanja untuk sekolah kristenisasi itu, sementara dia menggunakan kerudung,” katanya.
Tuduhan itu segera terbantahkan dengan bukti nyata pendidikan dan kegiatan di lingkungan sekolahnya. “Ibu asrama siswa saja pakai jilbab, komposisi siswa dan guru muslim juga paling banyak sesuai komposisi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Isu itu akhirnya pupus setelah warga saya undang ke sini,” katanya.
Bukti itu kemudian membalik sikap warga setempat. “Sekarang malah banyak yang ingin daftar ke sini. Tapi, ya, sulit, karena kuota terbatas dan harus berasal dari wilayah yang berbeda,” katanya.
Kini dengan lahan yang berkembang hingga 14 hektare dan ratusan donatur yang tak pelit berbagi, Julianto tidak berpikir untuk mengembangkan kapasitas jumlah siswa atau pun membuka cabang sekolah di tempat lain. Di tahun angkatan yang kedelapan kini dia berpikir untuk mengentaskan kemiskinan dengan pembekalan keterampilan wiraswasta atau pun keterampilan kerja.
Menurutnya, hidup yang layak di atas garis kemiskinan akan mencegah siapa pun untuk mudah terprovokasi berbagai gerakan fanatis keagamaan, suku, ras maupun antargolongan. “Jika sejahtera maka orang tidak akan berpikir mau makan apa besok.”
“Ada banyak kebutuhan lain yang sudah bisa dipenuhi, seperti akses informasi lewat internet, media massa, koran, televisi. Maka doktrin seperti ISIS akan mudah ditepis dengan sendirinya karena mereka tahu informasi dan tak mudah terprovokasi. Bagaimana mereka mau mendukung ISIS jika mereka tahu ISIS berencana merobohkan Mekkah,” dia menambahkan.
Baca berita lain:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Saya jadi hapal doanya orang Hindu, Budha, Katolik, dan Islam. Karena yang bertugas harus memimpin doa sesuai agamanya. Sering juga bertanya tentang ritual ibadah, tetapi tidak mendiskusikan atau mencari yang paling baik karena itu bisa memicu pertengkaran,” katanya.